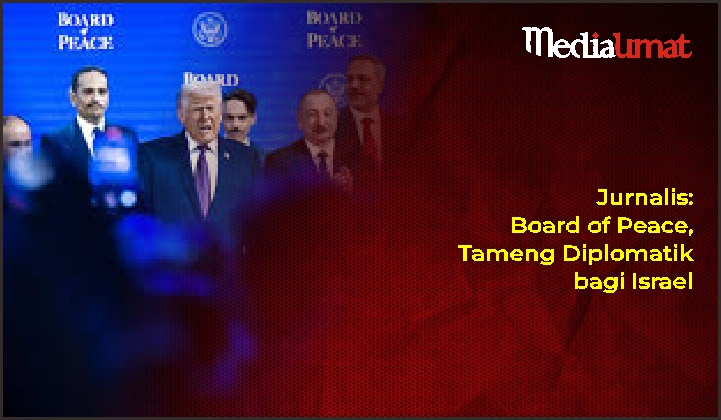TEFI Anggap Wajar Publik Khawatir dengan Sertifikat Tanah Elektronik

MediaUmat – Direktur The Economics Future Institute (TEFI) Dr. Yuana Tri Utomo menganggap wajar bila publik khawatir terkait diubahnya sertifikat tanah fisik menjadi sertifikat elektronik.
“Jadi, kekhawatiran publik terkait himbauan pemerintah untuk mengubah sertifikat tanah fisik menjadi sertifikat elektronik itu merupakan hal yang sangat wajar, terutama dalam konteks kepercayaan terhadap lembaga pengelola data seperti Badan Pertanahan Nasional ini,” bebernya dalam Kabar Petang: Ubah Sertifikat Tanah Jadi Digital, Siap-Siap Tanah Hilang Sekejap Jika Server Diretas? di kanal YouTube Khilafah News, Rabu (2/7/2025).
Terkait masalah tersebut, ia pun memberikan empat catatan penting. Pertama, transformasi digital jika tidak diiringi dengan kredibilitas sistem justru akan menjadi bumerang.
“Digitalisasi sertifikat tanah pada dasarnya langkah positif terutama untuk mengurangi potensi pemalsuan, kehilangan fisik dokumen sertifikat, terus mempercepat layanan. Namun keberhasilan digitalisasi ini sangat bergantung pada infrastruktur teknologi dan integritas institusi yang mengelolanya,” ungkap Yuana.
Kedua, ada kekhawatiran masyarakat tentang keamanan data dan potensi kebocoran. “Respon ini sangat logis ya,” cetusnya.
Karena, jelas Yuana, sudah ada beberapa kasus kebocoran data publik yang pernah terjadi di lembaga pemerintahan. Apalagi data pertanahan ini bersifat sangat sensitif, menyangkut kepemilikan, dan potensi nilai ekonominya yang besar.
“Jika sistem BPN belum memiliki rekam jejak kuat dalam pengelolaan data digital, maka wajar masyarakat menuntut jaminan sistem yang terenkripsi, aman dari serangan siber, terus jaminan transparansi mekanisme digitalisasinya, jaminan audit berkala oleh pihak independen itu,” tukasnya.
Ketiga, ada beberapa penelian publik bahwa BPN tidak rapi atau tidak konsisten mengelola data tanah. Misalnya tumpang tindih lahan, kemudian adanya sertifikat ganda atau proses birokrasi yang lambat, dan tidak transparan.
“Jika persoalan ini belum diselesaikan secara sistemik, maka digitalisasi ini justru bisa memindahkan kekacauan dari lemari arsip ke server digital,” kritiknya.
Jadi, ia simpulkan, digitalisasi ini bukanlah ide yang keliru. Akan tetapi, masyarakat punya hak untuk khawatir jika prosesnya yang dilakukan itu tanpa transparansi dan tanpa jaminan keamanan, apalagi tidak ditambah dengan perbaikan kelembagaan.
“Sebelum mengubah sertifikat menjadi elektronik yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah tata kelola, terus kemudian integritas data dan kredibilitas BPN itu sendiri. Karena ini adalah problem sistemik ya terkait tata kelola dalam pelayanan terkait dengan riayah suunil ummah (pemeliharaan urusan umat). Apalagi kalau kita ingat mayoritas tanah di nusantara ini adalah tanah umat Muslim yang dulu ketika Islam datang ke negeri ini datang dengan kedamaian,” bebernya.
Pungutan Biaya
Selain itu, ia juga mempertanyakan pungutan biaya Rp50.000 untuk alih media sertifikat tanah fisik ke sertifikat elektronik.
“Pertanyaan itu penting diajukan karena menyangkut asas keadilan dan logika kebijakan publik. Nah, digitalisasi ini kan program negara. Mengapa dibebankan ke warga? Logikanya kan begitu,” tanyanya retoris.
Nah, ungkapnya, digitalisasi sertifikat tanah ini merupakan inisiatif pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data pertanahan.
“Karena memang ini termasuk program strategis nasional,” ucapnya.
Maka, tegasnya, seharusnya didanai oleh APBN bukan dibebankan ke rakyat, apalagi terhadap hak milik yang sudah sah.
“Kan sudah puluhan tahun mungkin, bahkan sejak nenek moyang tanah itu menjadi tanah rakyat, tanah yang dokumennya sah, sertifikatnya jelas,” ujarnya.
Ia menilai, dengan adanya pungutan tersebut terkesan memindahkan tanggung jawab negara kepada individu.
“Itu program awalnya memang dari pemerintah yang menggulirkan kebijakan sehingga sertifikat tanah sebagai dokumen hukum atas hak milik, maka bukan jasa atau layanan ya jasa atau layanan baru,” tuturnya.
Menurutnya, hal ini sangat problematik karena biaya itu tidak dibedakan berdasarkan kondisi ekonomi. Padahal sebagian besar warga tidak mendapat manfaat langsung atau tambahan dari digitalisasi itu, belum lagi transparansi pemanfaatan dana tersebut juga belum jelas.
“Ya begitulah ketika tata kelola negara ini berbasis pada kapitalisme ya,” pungkasnya.[] Novita Ratnasari
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat